 |
| Abjad Suku Aborigin Australia |
Fokussumatera.com - Bahasa merupakan inti dari identitas budaya, spiritualitas, dan pengetahuan kolektif suatu masyarakat. Dalam konteks masyarakat Aborigin di Australia, bahasa berfungsi lebih dari sekadar alat komunikasi; bahasa adalah penghubung dengan tanah leluhur, cara pewarisan pengetahuan ekologis, serta penopang struktur sosial.
Fakta bahwa dari lebih dari 250 bahasa dengan sekitar 600 dialek yang pernah ada, kini hanya tersisa kurang dari 120 bahasa dan sebagian besar dalam kondisi terancam punah, mencerminkan dampak mendalam kolonisasi terhadap warisan linguistik tertua di dunia (AIATSIS, 2020). Penurunan jumlah bahasa ini bukanlah fenomena alamiah, melainkan hasil dari sejarah panjang diskriminasi dan kebijakan asimilasi yang dilakukan sejak akhir abad ke-18 (Pramudya & Ribawati, 2025).
Kolonisasi Inggris yang dimulai pada tahun 1788 membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Aborigin. Kehadiran bangsa Eropa tidak hanya berarti masuknya teknologi dan sistem pemerintahan baru, tetapi juga proses penggusuran, peminggiran, dan kekerasan yang dialami oleh masyarakat asli.
Dampak langsung dari kolonisasi meliputi pemaksaan gaya hidup baru, hilangnya ruang budaya, dan pelemahan tradisi lisan yang selama ribuan tahun menjadi sarana utama pelestarian bahasa (Pramudya & Ribawati, 2025). Hilangnya tanah adat sebagai pusat kehidupan sosial dan spiritual tidak hanya berimplikasi pada hilangnya kedaulatan, tetapi juga mempercepat keruntuhan penggunaan bahasa sehari-hari.
Kebijakan Stolen Generations yang berlangsung sejak awal abad ke-20 semakin memperparah kondisi. Anak-anak Aborigin diambil paksa dari keluarganya untuk diasuh dalam lingkungan Eropa. Situasi ini membuat mereka kehilangan kesempatan untuk belajar bahasa leluhur, karena yang diajarkan hanyalah bahasa Inggris dan budaya dominan (Broome, 2002). Kehilangan generasi penerus penutur alami inilah yang menyebabkan banyak bahasa punah hanya dalam satu atau dua generasi.
Kebijakan diskriminatif seperti Immigration Restriction Act pada tahun 1901 atau White Australia Policy memperkuat marginalisasi. Kebijakan ini tidak hanya membatasi imigrasi non-Eropa, tetapi juga menghapus peran Aborigin dari kerangka pembangunan bangsa. Bahasa dan budaya mereka dianggap tidak relevan dengan visi negara modern (Kamelia et al., 2022). Dampaknya, masyarakat Aborigin dipaksa menggunakan bahasa Inggris di ranah publik, sementara bahasa asli tidak mendapat pengakuan dalam pendidikan maupun pemerintahan.
Hilangnya bahasa tidak hanya berarti hilangnya kosakata atau tata bahasa, melainkan hilangnya cara pandang dunia. Bahasa Aborigin mengandung pengetahuan ekologis yang mendetail, termasuk nama-nama tanaman obat, hewan, sungai, dan lanskap alam yang tidak dapat diterjemahkan sepenuhnya ke dalam bahasa Inggris.
Dalam wawancara dengan BBC, seorang penutur bahasa Marone menegaskan keterikatan antara bahasa, tanah, dan kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan, “the land is my land and it’s where the language come from… everything we see that’s language, everything that moves that’s language, all the food source and waters rivers they all have names and that’s how we can describe what it is” (BBC, 2023). Pernyataan ini menunjukkan bahwa bahasa Aborigin menyatu dengan lanskap alam, sesuatu yang sulit dipahami atau dijelaskan hanya dengan bahasa Inggris.
Meskipun sebagian besar bahasa Aborigin berada dalam status kritis, terdapat upaya penyelamatan yang semakin berkembang. Di wilayah Northern Territory dan Arnhem Land, bahasa-bahasa seperti Yolŋu Matha, Pitjantjatjara, Arrernte, dan Warlpiri masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah-sekolah di wilayah ini mulai memperkenalkan pendidikan dwibahasa agar anak-anak bisa belajar bahasa leluhur di samping bahasa Inggris (AIATSIS, 2020).
Selain itu, komunitas juga beradaptasi dengan modernitas. Contohnya, ketika mobil pertama kali masuk ke wilayah masyarakat Marone, mereka memberi nama “quaderi,” yang terinspirasi dari suara mesin kendaraan tersebut. Hal ini menunjukkan kemampuan bahasa Aborigin untuk berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan identitas (BBC, 2023).
Bahasa Aborigin adalah suara leluhur yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun, namun kini berada di ambang kepunahan akibat kolonisasi, kebijakan diskriminatif, dan modernisasi. Hilangnya bahasa berarti hilangnya pengetahuan ekologis, identitas, serta spiritualitas masyarakat Aborigin.
Namun, melalui program pendidikan dwibahasa, dokumentasi akademik, dan gerakan komunitas, masih ada harapan untuk menyelamatkan bahasa-bahasa ini. Harapan yang disampaikan mencerminkan perjuangan panjang untuk memastikan generasi mendatang tetap bisa berbicara dengan suara leluhur mereka. Menyelamatkan bahasa Aborigin bukan hanya menyelamatkan kata-kata, tetapi juga menyelamatkan sejarah, pengetahuan, dan jati diri masyarakat tertua di dunia.
Sumber:
AIATSIS. (2020). National Indigenous Languages Report. Canberra: Australian Government.
BBC. (2023). Indigenous Australian languages and survival. BBC Interview Archive. https://youtu.be/ZwSXFvDDjYE?si=x_dtgTFgPxzFDBMw
Bowern, C., & Atkinson, Q. D. (2012). Computational phylogenetics and the internal structure of Pama–Nyungan. Language, 88(4), 817–845.
Broome, R. (2002). Aboriginal Australians: A History Since 1788. Allen & Unwin.
Evans, R., Saunders, K., & Cronin, K. (2003). Race Relations in Colonial Queensland: A History of Exclusion, Exploitation and Extermination. University of Queensland Press.
Kamelia, I. F., Nurhasanah, L., Al-Zahra, N., Bachtiar, O. S., Aulia, Y. I., & Rohman, I. R. (2022). Penerapan Kebijakan Immigration Restriction Act di Australia (1901–1973). Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah, 5(1), 70–84. http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari/article/view/5461
Levinson, S. (2003). Space in Language and Cognition. Cambridge University Press.
Pramudya, H. A., & Ribawati, E. (2025). Dampak Kolonisasi Terhadap Penduduk Asli Australia: Sejarah dan Implikasinya. Student Scientific Creativity Journal, 3(1), 1–9. https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/sscj/article/view/4587
https://pin.it/3ncT9IlOb (pinterest)
Penulis : Rasmulianda (Mahasiswi Sastra Inggris Unand)















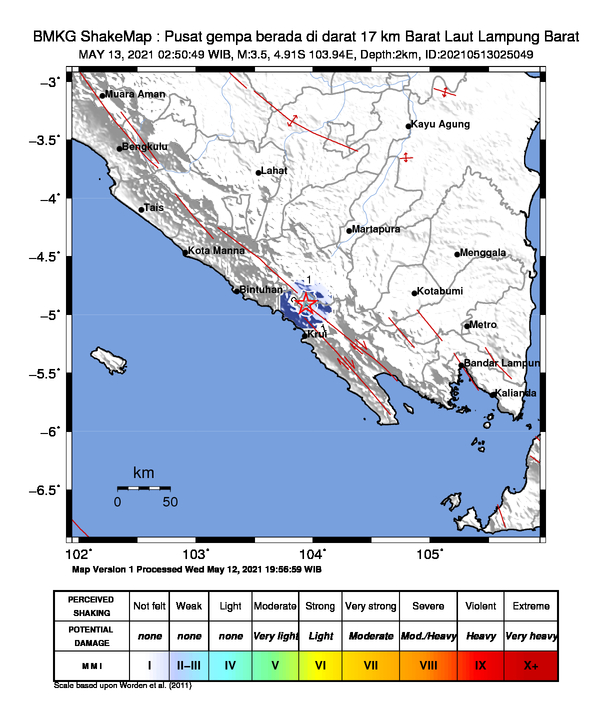





 SEMOGA BERMANFAAT!
SEMOGA BERMANFAAT!
No comments:
Post a Comment